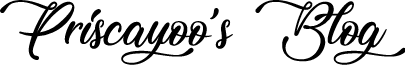Tulisan ini sebagai syarat masuk pramuda Forum Lingkar Pena cabang Bogor kala itu. Maksudnya sih cerpen. Setelah belajar apa itu cerpen sebenarnya, ternyata eh ternyata ini bukan termasuk kategori cerpen karena tak ada konflik di dalamnya wkwk. Oiya, mohon maaf kalau nama dalam cerita tidak disamarkan. Mohon maaf juga kalau ada kesamaan cerita dengan yang sebenarnya. Namanya juga penulis pemula, belum ahli "konspirasi" ._.v
#LatePost
Ada
apa sih dengan orang Jepang? Caranya
menaati aturan, caranya mendidik, caranya tekun belajar, caranya menghargai
orang, caranya bersabar mengantri, bahkan caranya duduk, juga caranya
mengenakan sepatu. Hampir – hampir semua adab mereka begitu mengagumkan, seperti
adab – adab yang sebenarnya banyak dianjurkan dalam Islam. Padahal, kita tahu
bahwa jarang dari masyarakat Jepang yang benar – benar memeluk suatu agama.
Biasanya, agama hanya dijadikan ritual pernikahan atau kematian. Begitu sih kabar yang sering kudengar.
Betapa
kebiasaan baik mereka merupakan suatu warisan yang sangat berharga. Mengingat
cara mereka menjalani keseharian, aku jadi ingin bercerita tentang salah
seorang Jepang yang pernah kukenal sebelumnya. Aku bertemu dengannya setahun
yang lalu, saat aku dan teman – teman mahasiswa semester 6 Institut Pertanian
Bogor (IPB) sedang diutus ke berbagai pelosok desa untuk menjalani Kuliah Kerja
Nyata (KKN) selama dua bulan. Inilah cuplikan kisahku di sebuah desa bernama
Karangmulya, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah.
***
“Nah,
ini nih. ‘Anak’ Bapak yang udah lama dikangenin akhirnya dateng juga. Namanya
Keio. Pernah KKN di sini juga, program dari Six
University Initiative Japan – Indonesia (SUIJI). Cuma dua minggu sih, tapi
cukup padet dan berkesan”, Pak Kepala Desa (Kades) dengan wajah sumringahnya
menggandeng seorang pria seumuran kami bernama Keio dan memperkenalkannya pada
kami.
“Wah,
selamat datang...”, Nanas dan kami menyambutnya.
Keio
membalas senyuman kami dengan lebih lebar, kemudian membungkukkan badan. Saat tersenyum,
mata orang Jepang memang seperti menghilang. Namun, caranya membungkukkan badan
tidak seperti orang Jepang di televisi yang begitu sempurna seperti gerakan
rukuk. Biasa saja kok, baguslah.
“Ini
lho. Foto Keio ada di kalender ini. Ada foto mahasiswa anggota SUIJI yang
lainnya juga”, terang Pak Kades.
Petang
itu, kami berkenalan di antara hiruk pikuk suara pertarungan Naruto melawan gang Akatsuki. Animasi Jepang itu adalah
tontonan favorit si Yasfa, anak Pak Kades yang paling kecil.
“Keio,
kenalkan. Namaku Prisca”, kataku memulai perkenalan.
“Sebentar
– sebentar”, kata Keio yang segera berpaling menuju tasnya, kemudian kembali
dengan sebuah pena dan buku notes kecil di genggaman. “Siapa?”, tanyanya dengan
posisi pena yang terangkat.
“Mau
dicatat?”, tanyaku heran.
“Ya!
Biar tidak lupa”, jelasnya dengan logat khas Jepang yang lucu, seperti ada
penambahan huruf hamzah di tiap akhir kata.
“Pris-ca”,
aku mengeja perlahan.
Namun,
dahinya mengerut dan penanya masih belum juga digerakkan.
“Hmm,
sini deh...”, aku mengambil alih pena dan buku notesnya, kemudian menuliskan
namaku sendiri : p-r-i-s-c-a. Tidak hanya bagi orang Jepang seperti Keio,
namaku memang seringkali sulit dieja oleh banyak orang. Jadi, wajarlah.
“Nah,
aku Yen-dar. Ini A-fa, yang ini Na-nas”, Yendar memperkenalkan diri, kemudian
Afa dan Nanas juga diperkenalkan sambil dirangkul bahunya.
Keio
mencatat dengan cepat, tak boleh ada yang tertinggal. “Nanas?”, tanyanya
memastikan. Mungkin, ia jadi teringat dengan nama buah.
“Iya,
dari Nastuti. Lucu kan?”, jelas Nanas.
“Nah,
kalo saya Crisna, ini Herdian, dan itu Iqbal”, Crisna memperkenalkan dengan
santai tanpa pengejaan, kemudian berjabat tangan.
“Hai,
Keio”, Herdian menyapa sambil menjabat tangan, disusul Iqbal.
Aku sempat membayangkan, seru juga ya
jika kita mendata semua nama yang pernah kita temui dalam hidup. Aku jadi
penasaran, ada berapa nama ya yang tercantum di notes kecil itu?
***
“Maaf sudah buat Keio bangun. Pindah
dulu ya tidurnya”, kataku dengan membawa semangkuk besar sayur.
Kuletakkan hidangan sahur tersebut
di atas karpet lesehan yang baru saja ditiduri Keio, disusul oleh teman – teman
yang membawa sebakul nasi dan peralatan makan lainnya. Sebenarnya, kasur di
sini memang kurang cukup dengan adanya kami yang cukup banyak ini. Teman laki –
laki kami biasa tidur di ruang tamu dengan selimut dan bantal seadanya, meski
suhu udara saat malam sangat dingin. Wajar saja karena ketinggian tempat desa
ini mencapai 939 m dpl, termasuk dalam wilayah pegunungan.
“Masih malam, sudah bangun? Mau
makan?”, tanya Keio dengan mata sipit yang semakin disipitkannya.
Dia ikut sahur bersama kami. Kata
Pak Kades, Keio memang biasa ikut – ikutan puasa. Mungkin begitulah caranya
menghargai orang di sekelilingnya. Kali ini, ia tak bertanya terkait menu
makanan. Ia juga tidak mencatatnya seperti yang ia lakukan saat berbuka puasa
kemarin. Mungkin karena ia sudah tahu nama makanan yang terhidang kali ini dan
ia juga terlalu mengantuk untuk berpikir.
***
“Wah, tinggi banget Pohon Cengkeh”,
kataku kegirangan setelah Pak Kades menjelaskan.
Yang lain mungkin heran, aku pun
heran, “Sebenarnya jurusan si Prisca ini
pertanian bukan sih? Kok apa – apa (jenis - jenis tanaman) baru tahu”. Biasanya
aku berdalih bahwa aku tidak mempelajari semua tanaman, ada yang masuk ranah
tanaman kehutanan, kan. Lagipula,
sebagian besar masa hidupku kan dihabiskan
di perkotaan yang jarang ditemui aneka tanaman. Maklumi saja lah.
Kali ini, lembaran notes Keio
dipenuhi nama – nama tanaman dari ladang Pak Kades. Ia sempat bertanya tentang
proses penanaman cabai hibrida IPB yang telah kulakukan.
“Awalnya persemaian lho. In English is pre-nursery, main nursery,
transplanting. Tahu?”, jelasku.
“Tidak tahu. Aku lebih tahu bahasa
indonesia daripada inggris”, ia ingin mencatat, tetapi masih butuh penjelasan.
Kujelaskan saja dengan bahasa isyarat yang
ekspresif dengan sedikit kata keterangan. “Benih/biji, tebar – tebar, tumbuh
kecil, pindah ke pot besar/ bedeng sebenarnya”.
Ia sedikit tertawa, kemudian mencatat
sepahamnya.
***
Aku
juga suka mencatat kejadian – kejadian di tiap harinya secara singkat dan
menulis rencana untuk hari berikutnya. Namun, dibandingkan dengan catatan Keio
yang sedetail itu tentunya aku masih kalah. Itulah yang membuatku terkesan
dengan orang Jepang yang satu ini, yaitu dari caranya menghargai dan mengikat
ilmu yang ia temui. Suatu hari, sahabat Rasulullah SAW bernama Ali bin Abi
Thalib r.a. pernah berkata, “Ikatlah ilmu dengan menuliskannya”. (Ukh Pymaisha)